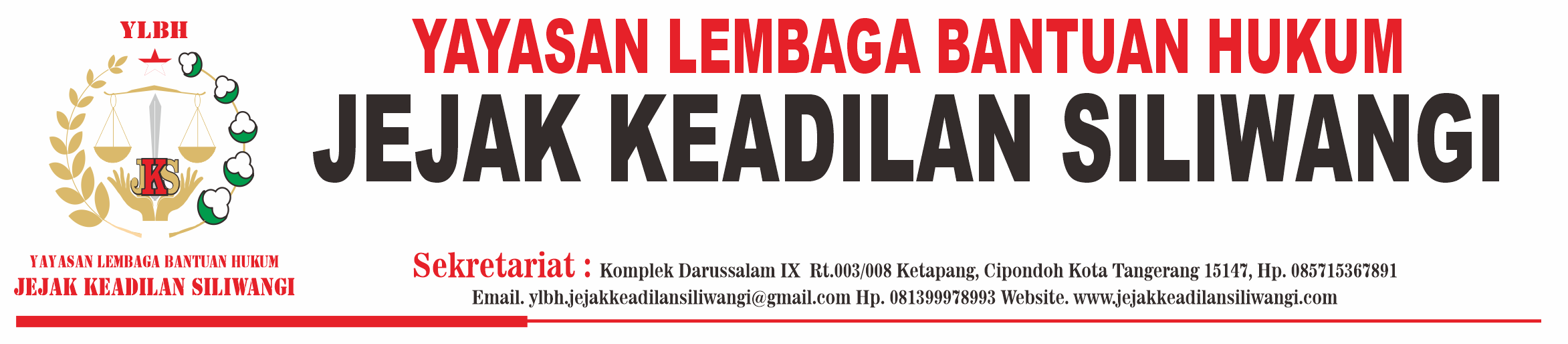Oleh: Rioberto Sidauruk, Dewan Penasihat rakyatkita.id dan Surat kabar umum dan online Berantas Korupsi
BK, Jakarta,- Kebebasan pers adalah salah satu capaian terbesar Reformasi 1998. Namun, lebih dari dua dekade setelah tumbangnya rezim otoriter, profesi jurnalis di Indonesia masih menghadapi ancaman serius.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sedikitnya 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak Januari hingga Agustus 2025.
Insiden terbaru saat demonstrasi di Jakarta pada akhir Agustus memperlihatkan jurnalis masih menjadi target pemukulan, intimidasi, dan perusakan alat kerja.
Jurnalis foto ANTARA dan Tempo turut menjadi korban. Fakta ini menunjukkan kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang masih rapuh di lapangan.
Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat tajam. Setelah reformasi, tercatat 1.398 penerbitan baru. Namun hingga 2000, hanya 487 yang bertahan.
Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi atas pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.
Selain bergugurnya media, kekerasan terhadap jurnalis juga menonjol. Catatan AJI menunjukkan setelah reformasi kekerasan justru meningkat: 42 kasus (1998), 74 kasus (1999), 115 kasus (2000), lalu menurun menjadi 95 (2001), 70 (2002), dan 59 (2003). Data ini menegaskan bahwa kebebasan pers hadir, tetapi selalu diiringi ancaman.
Kebebasan Pers dan Demokrasi
Era Presiden Habibie memberi napas segar kebebasan pers lewat lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Gus Dur dikenal sangat permisif, menolak segala bentuk pembredelan.
Pada era Megawati, dinamika politik membuat relasi pemerintah–media tidak selalu mulus. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, pers relatif bebas, meski kritik kadang dibalas gugatan hukum.
Situasi berubah signifikan di era Joko Widodo, ketika indeks kebebasan pers merosot karena kekerasan, intervensi, hingga kriminalisasi jurnalis dengan UU ITE.
Kini, di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, tantangan semakin besar. Catatan AJI tentang puluhan kasus kekerasan pada 2025 membuktikan ancaman itu nyata.
Ironisnya, semua ini terjadi ketika pers sangat dibutuhkan untuk menghadirkan informasi kredibel di tengah banjir disinformasi.
Mark Twain pernah berkata, “Kebebasan pers hanya dijamin untuk mereka yang memilikinya.” Kutipan ini menyindir kenyataan bahwa jurnalisme sering dikebiri kekuasaan, padahal masyarakat bergantung pada kerja jurnalis untuk mengetahui kebenaran.
Christiane Amanpour, jurnalis senior CNN, juga mengingatkan bahwa tanpa pers yang bebas, masyarakat akan terjebak dalam kegelapan informasi dan demokrasi melemah.
Bill Kovach, penulis The Elements of Journalism, menambahkan bahwa fungsi utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya agar warga bisa membuat keputusan bebas dan mandiri.
Pandangan ini menegaskan bahwa ancaman terhadap jurnalis bukan sekadar urusan profesi, melainkan soal kelangsungan demokrasi.
Sejalan dengan itu, pakar hukum pers Todung Mulya Lubis menekankan bahwa Undang-Undang Pers harus ditegakkan konsisten sebagai lex specialis.
Tanpa keberanian negara memberi perlindungan hukum tegas bagi jurnalis, semangat kebebasan pers hanya akan jadi retorika.
Pers Indonesia juga memiliki fungsi diplomasi. Dalam menyajikan berita, media perlu menghadirkan sudut pandang nasionalisme, bukan sekadar menyalin agenda asing.
Fungsi pers sebagai jendela dunia jangan dilupakan, apalagi di tengah banyaknya media internasional yang beroperasi di Indonesia.
Dengan cara ini, publik tetap bisa terhubung dengan dinamika global tanpa kehilangan perspektif kebangsaan.
Menguatkan Perlindungan Pers
Kelemahan utama ada pada implementasi UU Pers. Pasal 8 menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, tetapi kenyataannya aparat masih sering menjadi pelaku kekerasan.
Revisi diperlukan untuk mempertegas sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi atau menyerang jurnalis. Bukan sekadar denda administratif, melainkan hukuman penjara agar ada efek jera.
Pasal 18 yang memuat ketentuan pidana juga perlu diperkuat, sehingga kekerasan terhadap jurnalis tidak lagi dianggap sepele.
Solusi lain adalah memperluas definisi “pers” dalam UU, agar tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik konvensional.
Di era digital, banyak jurnalis bekerja melalui media daring, media sosial, hingga kanal independen. Tanpa perluasan definisi, kelompok ini tetap rentan tanpa payung hukum.
Di sisi lain, Dewan Pers juga perlu diperkuat kewenangannya. Selama ini lembaga ini hanya bersifat mediasi. Idealnya, Dewan Pers memiliki otoritas eksekusi, sehingga rekomendasi mereka memiliki kekuatan mengikat.
Namun, regulasi saja tidak cukup. Literasi publik terhadap media harus ditingkatkan. Masyarakat perlu kritis membedakan berita kredibel dari kabar bohong.
Kolaborasi jurnalis, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil bisa memperluas pengawasan publik terhadap praktik kekerasan sekaligus meningkatkan kualitas jurnalisme.
Penguatan jurnalisme investigasi yang berani dan akurat menjadi benteng melawan banjir hoaks.
Ada satu terobosan yang jarang dibicarakan: perlindungan digital bagi jurnalis. Di tengah serangan siber, peretasan, dan doxing, jurnalis butuh perlindungan fisik sekaligus infrastruktur digital yang aman.
Pemerintah bersama komunitas pers bisa membangun sistem enkripsi nasional untuk data jurnalis serta menyediakan pusat respons darurat digital.
Dengan begitu, serangan dunia maya yang bertujuan membungkam jurnalis bisa dihadapi secara sistematis.
Membicarakan kebebasan pers bukan sekadar soal jurnalis, melainkan tentang masa depan demokrasi. Kekerasan terhadap wartawan adalah kekerasan terhadap hak publik untuk tahu.
Jika negara sungguh menghargai demokrasi, melindungi jurnalis harus menjadi prioritas utama. Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan kehilangan denyut nadinya. ( Rioberto Sidauruk, S.H.,M.H )