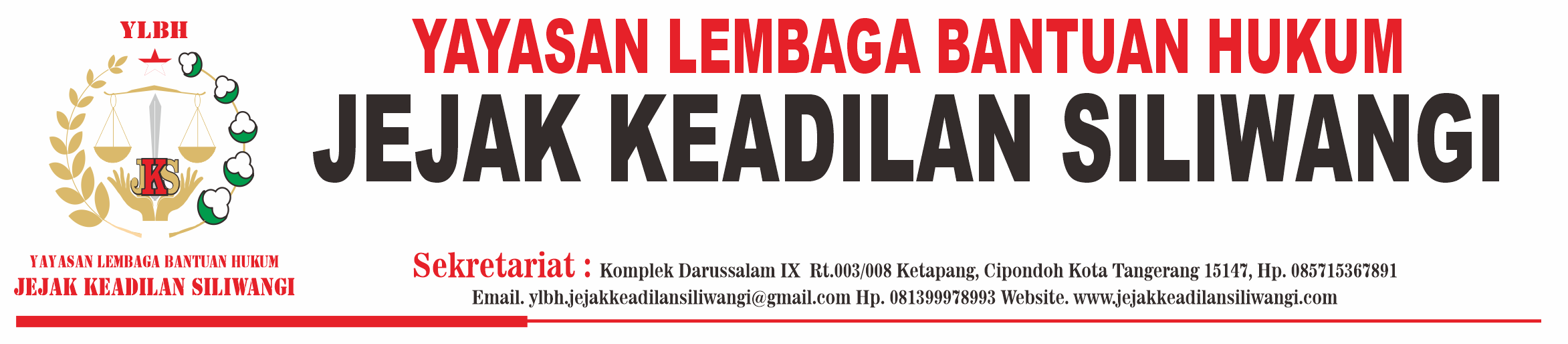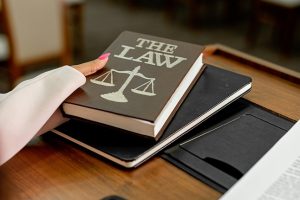Oleh: Rioberto Sidauruk – Pemerhati Sejarah.
BK, Jakarta,- Bangsa ini tengah melangkah di ambang jurang, bukan karena krisis ekonomi atau politik semata, melainkan karena kita sedang membunuh para penjaga ingatannya sendiri. Proyek penulisan ulang sejarah—sebuah ikhtiar mulia untuk merekatkan luka, mengembalikan narasi yang dicuri dari isu gender, masyarakat adat, dan korban konflik—justru dikoyak-koyak oleh kecurigaan publik. Yang diperdebatkan bukan lagi kebenaran, melainkan hakikat keahlian itu sendiri. Kita menjadi korban epidemi global: kematian keahlian (The Death of Expertise), di mana otoritas ilmu pengetahuan diinjak-injak oleh kesombongan kolektif yang berujung pada pengkhianatan intelektual.
Ilusi Setara: Ketika Algoritma Menggantikan Otak
Tom Nichols, dalam bukunya yang tajam, membongkar racun zaman ini: demokratisasi informasi yang kebablasan telah melahirkan generasi yang menyangka diri “pakar” hanya setelah membaca satu artikel di internet. Media sosial mengukuhkan ilusi itu—setiap celoteh, tak peduli dangkalnya, dianggap sejajar dengan riset puluhan tahun. Padahal, rekonstruksi sejarah bukanlah kerja copy-paste belaka. Ia memerlukan penggalian arsip kolonial yang tersembunyi di Den Haag misalnya, verifikasi lisan para saksi yang nyaris punah, dan dekonstruksi mitos politik Orde Baru yang membatu. Menganggap semua ini “sekadar menulis buku” adalah penghinaan telak terhadap sebuah disiplin ilmu yang membutuhkan dedikasi seumur hidup.
Dunning-Kruger Effect: Saat Ketidaktahuan Menjelma Kepercayaan Diri Palsu
Fenomena paling jahat yang diungkap Nichols adalah ketika ketidaktahuan justru melahirkan kepercayaan diri palsu yang membabi buta. Lihatlah komentar-komentar pedas di jagat maya: “Ah, sejarawan cuma korup! Saya bisa teliti sendiri lewat YouTube.” Ini bukan kritik yang membangun, melainkan pembunuhan karakter terhadap peradaban itu sendiri. Di negeri ini, gelar profesor sejarah disamakan derajatnya dengan influencer yang hanya bermodal keberanian membacakan Wikipedia. Ironisnya, mereka yang paling tidak tahu justru paling lantang bersuara, memalu godam kebenaran hingga remuk tak berbentuk.
Politisasi Sejarah: Kuburan Massal Faktualisme
Nichols dengan tegas menyatakan: ketika politik mengintervensi keahlian, yang mati pertama kali adalah fakta. Proyek sejarah di Indonesia saat ini dikepung dua front yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, kaum konservatif berteriak, “Jangan sentuh pahlawan kami!” Seolah-olah sejarah adalah patung beku yang tak boleh disentuh. Di sisi lain, kaum progresif menuntut, “Bongkar semua sampai ke akar!” tanpa memahami kompleksitas dan metodologi penelitian sejarah. Para sejarawan yang berintegritas pun terjepit—dituduh “pengkhianat bangsa” jika tak membenarkan mitos-mitos usang, atau dicap “agen asing” jika berani membongkar fakta kelam yang menyakitkan. Padahal, tugas utama mereka hanya satu: meneliti, bukan membangun monumen dogma yang menyesatkan.
Moral Injury: Luka Tak Terlihat di Balik Layar Arsip
Ada darah yang tak terlihat dalam pertempuran ini: pengkhianatan publik secara sistematis meracuni jiwa para ahli. Bayangkan penderitaan seorang profesor yang menghabiskan 20 tahun meneliti arsip gerakan perempuan 1965, hanya untuk karyanya disebut “proyek fiktif Rp 9 miliar” oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau tim arkeolog yang gigih menemukan situs pembantaian 1966 di Jawa Timur, tapi masyarakat justru lebih percaya video TikTok yang menyangkal temuan mereka. Ini bukan sekadar salah paham—ini adalah pengkhianatan intelektual (moral injury) yang membunuh gairah meneliti, mengikis motivasi, dan secara perlahan tapi pasti, membungkam suara-suara kebenaran.
Jalan Keluar: Revolusi Penghargaan atau Kematian Kultural
Indonesia harus segera memilih: melanjutkan bunuh diri kultural dengan meremehkan keahlian, atau melakukan revolusi besar-besaran dalam penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi kelangsungan identitas bangsa. Kita perlu memaksa transparansi, bukan hanya sebatas hasil akhir. Publik harus diajak melihat langsung proses di balik penulisan sejarah—mulai dari debat metodologi, kesulitan mengakses arsip yang tersembunyi, hingga pergulatan etika saat mewawancarai korban. Jadikan sejarah tontonan publik, bukan sekadar barang jadi yang tiba-tiba muncul dan harus diterima mentah-mentah. Dengan begitu, kecurigaan dapat diminimalisasi, dan pemahaman akan kompleksitas riset akan tumbuh.
Lebih dari itu, kita harus berani menghancurkan mitos busuk bahwa “semua pendapat itu setara.” Pendidikan kita harus secara tegas mengajarkan: “Tidak! Pendapatmu tentang G30S, yang hanya bermodal tontonan YouTube, tidak sejajar dengan penelitian Asvi Warman Adam yang berdasarkan puluhan tahun riset mendalam!” Teori Nichols tentang literasi informasi harus menjadi kurikulum wajib yang membentuk cara berpikir kritis generasi mendatang. Selain itu, sudah saatnya kita menyita panggung dari para politisi dan influencer yang gemar mengutak-atik sejarah demi kepentingan sesaat. Larang mereka berkomentar tentang sejarah tanpa mengutip jurnal akademik atau karya-karya sejarawan terkemuka. Sejarah bukan lapak dagangan politik atau arena hiburan; ia adalah ruang ICU bangsa yang membutuhkan penanganan serius dari ahlinya. Beri panggung utama kepada para sejarawan, bukan kepada mereka yang hanya mencari sensasi.
Epilog: Untuk Apa Kita Memelihara Pakar?
Kita membayar dokter saat tumor menggerogoti tubuh. Kita membayar insinyur saat jembatan retak. Lalu mengapa kita begitu pelit membayar dan menghargai para penjaga memori kolektif? Sejarah yang ditulis oleh pakar bukanlah sekadar buku usang; ia adalah vaksin melawan amnesia bangsa, peta untuk menghindari jurang konflik yang pernah terjadi, dan cermin yang memaksa kita berani melihat noda-noda gelap dalam diri kita sendiri.
Jika hari ini kita meremehkan mereka, besok anak cucu kita akan menggali kubur identitasnya di tumpukan hoaks dan mitos yang menyesatkan. Menolak keahlian sejarawan bukan kritik—itu bunuh diri. Dan ironisnya, Indonesia sedang mengasah pisau untuk melakukannya sendiri. ( Rioberto )